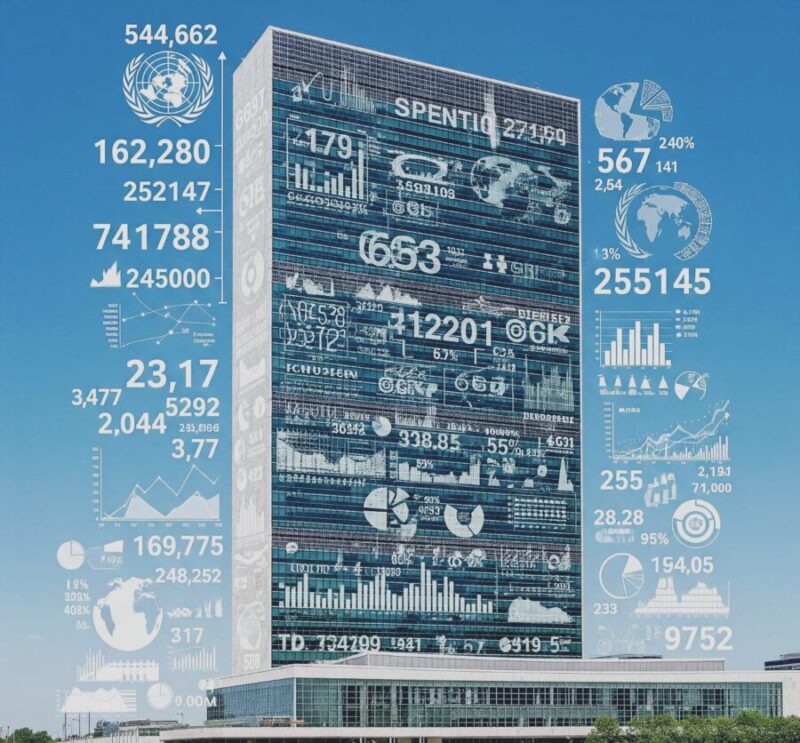Banyak sejarawan menyebut “Sejarah adalah milik mereka yang menang”. Barangkali dalam era digital dan big data, kutipan itu perlu kita revisi: ekonomi adalah milik mereka yang menguasai angka. Angka-angka bukan lagi sekadar refleksi realitas, melainkan instrumen kekuasaan yang bisa mengatur persepsi, membangun optimisme semu, bahkan menutupi krisis.
Pramoedya.id: Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen year on year. Angka yang cukup manis, seolah Indonesia sedang berada di jalur pertumbuhan stabil.
Namun, di jalan-jalan kota, antrean beras SPHP makin panjang, warung kopi sachet tetap penuh, dan pasar rakyat tak pernah sepi dari keluhan harga cabai yang kerap melambung. Antara angka di kertas dan kenyataan di lapangan, jurangnya semakin lebar.
Data yang Kontradiktif
Celios (Center of Economic and Law Studies) menangkap anomali serius. Di sektor manufaktur, BPS mengklaim tumbuh 5,68 persen, tapi Purchasing Managers’ Index (PMI) justru kontraksi. Artinya pelaku industri sendiri merasa produksinya menurun.
Kemudian, kontribusi manufaktur terhadap PDB justru menurun dibanding kuartal I. Inflasi pangan masih di atas 6 persen di beberapa daerah, dan daya beli rumah tangga stagnan.
Keganjilan ini membuat Celios menilai angka pertumbuhan 5,12 persen tidak masuk akal. Mereka lalu mengambil langkah berani: mengirim surat ke Komisi Statistik PBB dan United Nations Statistics Division (UNSD), meminta audit atas data BPS.
PBB pun merespons. Georges-Simon Ulrich, Ketua Komisi Statistik PBB, menyatakan laporan Celios akan diteruskan ke Divisi Statistik PBB untuk ditangani secara teknis. Singkatnya: isu ini resmi masuk agenda internasional.
Statistik sebagai Alat Kekuasaan
Kritik Celios tak bisa dipandang ringan. James C. Scott, dalam bukunya Seeing Like a State, menjelaskan bagaimana negara kerap menyulap statistik untuk “membuat masyarakat bisa dibaca dan diatur”. Data ekonomi dalam konteks ini bukan cuma angka, melainkan peta kuasa: siapa yang dianggap produktif, siapa yang disebut beban, siapa yang pantas dapat subsidi.
Kalau kata Sri Mulyani sih, guru adalah beban negara. Entahlah.
Di Indonesia, kita sudah pernah melihat pola serupa. Pada era Orde Baru, Indonesia dipuji sebagai “macan Asia” dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun kenyataannya, rakyat di desa banyak yang makan nasi aking, dan kesenjangan merajalela. Angka-angka dipakai sebagai kosmetik rezim. Kini, di era Prabowo, tudingan bahwa independensi BPS menurun membuat publik khawatir kita sedang mengulang sejarah.
Ilusi Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen ini ibarat tubuh yang tampak sehat karena polesan makeup, padahal organ dalamnya keropos. Jika industri manufaktur melemah, daya beli seret, dan inflasi pangan tinggi, dari mana angka pertumbuhan itu datang? Apakah dari sektor ekstraktif yang merusak lingkungan? Atau dari hitungan investasi yang hanya menguntungkan segelintir elite?
William Petty, bapak statistik modern, menyebut statistik sebagai political arithmetic. Artinya, sejak awal angka-angka memang bisa dipakai untuk menjustifikasi kekuasaan. Tidak heran jika hari ini angka pertumbuhan dipakai sebagai “penghiburan nasional” meskipun rakyat tahu kenyataannya jauh berbeda.
Rakyat di Antara Angka
Yang tragis adalah rakyat menjadi penonton dalam drama angka ini. Statistik memang tumbuh, tapi perut rakyat kerap keroncongan. Driver ojol kerja ekstra hanya untuk bayar cicilan motor, buruh pabrik hidup pas-pasan meski disebut bagian dari “industri yang tumbuh”, dan petani menjerit karena harga singkong jatuh sementara impor terus masuk.
Angka 5,12 persen ini seperti punya nafsu makan sendiri: kenyang sendirian, tanpa pernah berbagi dengan rakyat. Hidup di dokumen resmi, presentasi PowerPoint kementerian, dan rapat kabinet. Tapi gagal hidup di dapur keluarga biasa yang harus menghitung telur per butir untuk bertahan sampai akhir bulan.
Pertumbuhan untuk Siapa?
Dengan laporan Celios ke PBB, ‘kebohongan’ statistik Indonesia kini resmi masuk radar internasional. Dunia akan menilai, apakah Indonesia sungguh tumbuh, atau hanya tumbuh di kertas laporan.
Pertanyaannya sederhana: jika ekonomi benar-benar tumbuh, kenapa rakyat tidak ikut tumbuh? Atau jangan-jangan, pertumbuhan itu hanya ilusi. Pertumbuhan hanya terjadi di kepala penguasa yang butuh legitimasi, sementara rakyat dibiarkan kerdil?
Sejarah memang ditulis oleh yang menang. Dan dalam republik angka ini, pertumbuhan ekonomi tampaknya ditulis oleh mereka yang berkuasa atas statistik.(*)