Pramoedya.id: Bank Lampung sudah berdiri sejak 1966. Jika ia adalah seorang manusia, usianya sudah hampir 60 tahun, usia yang seharusnya sudah matang, bijaksana, dan punya aset di mana-mana. Namun sayangnya, selama puluhan tahun berdiri, bank kebanggaan masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai ini terasa hanya jalan di tempat.
Sementara bank daerah lain sudah berlari kencang membangun ekosistem digital, Bank Lampung masih asyik dengan pola lama: jadi “kasir raksasa” untuk gaji ASN.
Bagi ribuan ASN di Lampung, tanggal satu bukan sekadar hari gajian. Itu adalah hari “balapan”. Begitu notifikasi angka masuk ke rekening, jempol mereka segera bergerak lincah memindahkan saldo ke bank besar di Jakarta atau bank digital yang aplikasinya jauh lebih “waras”. Bank Lampung akhirnya tak lebih dari sekadar halte bus yang kumuh: tempat singgah yang terpaksa dikunjungi karena sistem, tapi tak ada yang mau menetap lama di sana.
Hampir Turun Kasta
Kondisi ini mencapai titik nadirnya ketika Bank Lampung hampir saja “turun kasta”. Dalam aturan perbankan, ada standar modal inti yang harus dipenuhi agar sebuah bank tetap bisa disebut bank umum yang gagah. Sialnya, Bank Lampung megap-megap memenuhi itu secara mandiri.
Langkah “numpang hidup” melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim di awal 2026 ini sebenarnya adalah pengakuan dosa yang nyata. Ini adalah bukti sahih bahwa setelah puluhan tahun berdiri, bank ini gagal mandiri.
Ia terpaksa “berlindung” di bawah ketiak bank daerah lain agar tidak turun kelas menjadi BPR. Ini bukan cuma soal angka di laporan keuangan, tapi soal harga diri sebuah provinsi yang katanya punya visi besar.
Monopoli yang Mematikan Naluri
Secara logika bisnis, Bank Lampung sebenarnya memegang “kartu mati” yang bikin bank swasta mana pun iri. Triliunan rupiah dana APBD wajib parkir di brankasnya, dan puluhan ribu nasabah “tawanan” (ASN) dipaksa menggantungkan hidup di sana.
Namun, hak istimewa ini justru jadi racun. Karena merasa nasabah tidak bisa lari, bank ini kehilangan naluri kompetisi. Bisnisnya jadi malas. Mereka hanya mengandalkan bunga kredit konsumtif dari skema potong gaji.
Bahasa gampangnya begini: bisnis bank itu ibarat kita dititipkan barang (uang), lalu barang itu kita sewakan ke orang lain supaya dapat untung. Nah, kalau uang ASN cuma “numpang lewat” lima menit lalu dikuras habis, Bank Lampung mau menyewakan apa? Akibatnya, mereka kering likuiditas untuk mendanai sektor produktif seperti pabrik atau perkebunan. Mereka akhirnya hanya jadi “kasir transit” yang kehilangan tenaga untuk memutar ekonomi daerah.
Isu Internal dan Krisis Kepercayaan
Keengganan masyarakat untuk setia bukan tanpa alasan. Coba ketik di mesin pencari Google: “Uang hilang di Bank Lampung”. Hasilnya adalah daftar panjang kasus dari tahun ke tahun, bahkan hingga kasus di 2025. Skandal skimming yang berulang menjadi noda yang sulit dihapus.
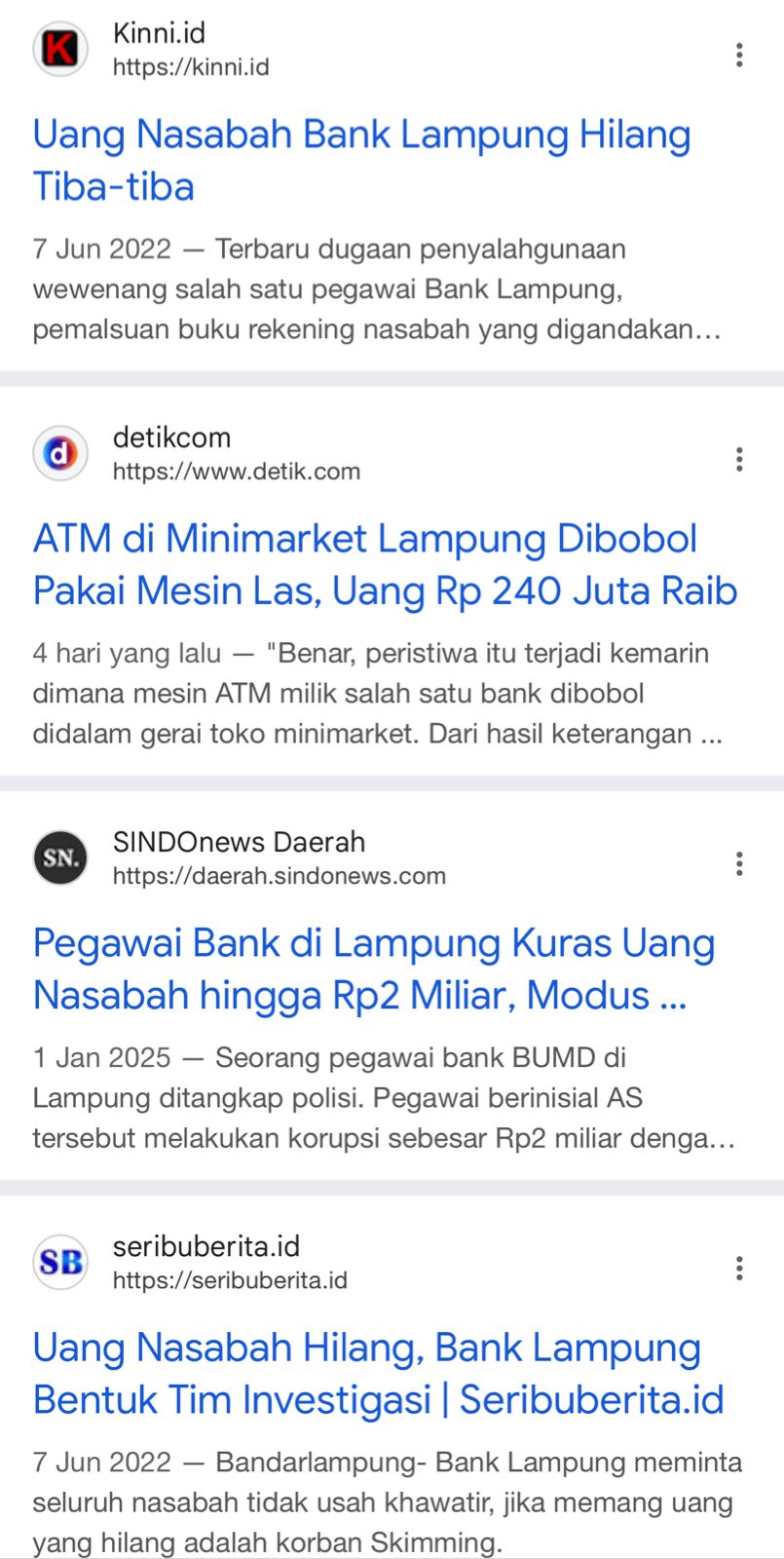
Masalah ini berakar pada internal yang sering kali terasa “gosong”. Sudah jadi rahasia umum bahwa posisi direksi dan komisaris sering kali diisi bukan oleh bankir yang lapar inovasi, melainkan oleh figur-figur yang aromanya lebih dekat ke kepentingan politik. Ketika direktur dipilih karena kedekatan, fokusnya bukan lagi membangun benteng siber yang antipembobolan, melainkan menjaga dividen tetap deras demi memoles citra pemegang saham. Investasi teknologi dikorbankan, sistem keamanan dibiarkan keropos, dan nasabah yang menanggung risikonya.
Angka di Atas Kertas yang “Barang Kecil”
Penulis sebenarnya cukup terhibur saat melihat catatan pembukuan Bank Lampung di tahun 2025. Di sana terpampang angka laba bersih yang mencapai miliaran rupiah, misalnya pada semester pertama yang menunjukkan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Manajemen mungkin menganggap ini adalah prestasi gemilang yang patut dirayakan dengan spanduk di mana-mana.
Namun, mari kita jujur: bagi bank sekelas BPD yang menguasai dana monopoli se-provinsi, angka-angka itu hanyalah “barang kecil”. Itu bukan prestasi hasil inovasi atau ekspansi pasar yang berdarah-darah, melainkan hasil “setoran otomatis” dari bunga pinjaman ASN yang memang tidak punya pilihan lain.
Sangat menggelikan jika pencapaian yang bersifat administratif itu dianggap sebagai kesuksesan besar, sementara di saat yang sama mereka harus menyerahkan kedaulatannya ke Bank Jatim melalui skema KUB hanya demi bertahan hidup.
Bank Lampung Mestinya Jadi Motor Swasembada Perekonomian
Saat ini, Provinsi Lampung sedang gagah-gagahnya menuju swasembada pangan. Sektor pertanian kita kuat, lumbung pangan kita terisi. Namun, swasembada pangan akan terasa hambar tanpa swasembada perekonomian.
Kita semua ingin Bank Lampung maju. Kita ingin bank ini menjadi motor utama yang mendanai petani, peternak, dan pengusaha lokal di pelosok Lampung. Kita ingin Bank Lampung berkembang pesat sehingga pembangunan lebih merata, tanpa kita perlu lagi jauh-jauh pinjam uang ke Bank BJB atau pihak luar. Visi “Lampung Maju” seharusnya berada tepat di depan mata jika bank daerahnya sehat.
Kita merindukan Bank Lampung yang bukan lagi tempat “numpang lewat”, tapi tempat rakyat Lampung menaruh masa depan dengan rasa aman.
Tanpa reformasi total yang membuang jauh-jauh campur tangan politik, Bank Lampung akan tetap menjadi raksasa yang lumpuh alias besar karena dipaksa sistem, tapi kerdil di mata rakyatnya sendiri. (*)













