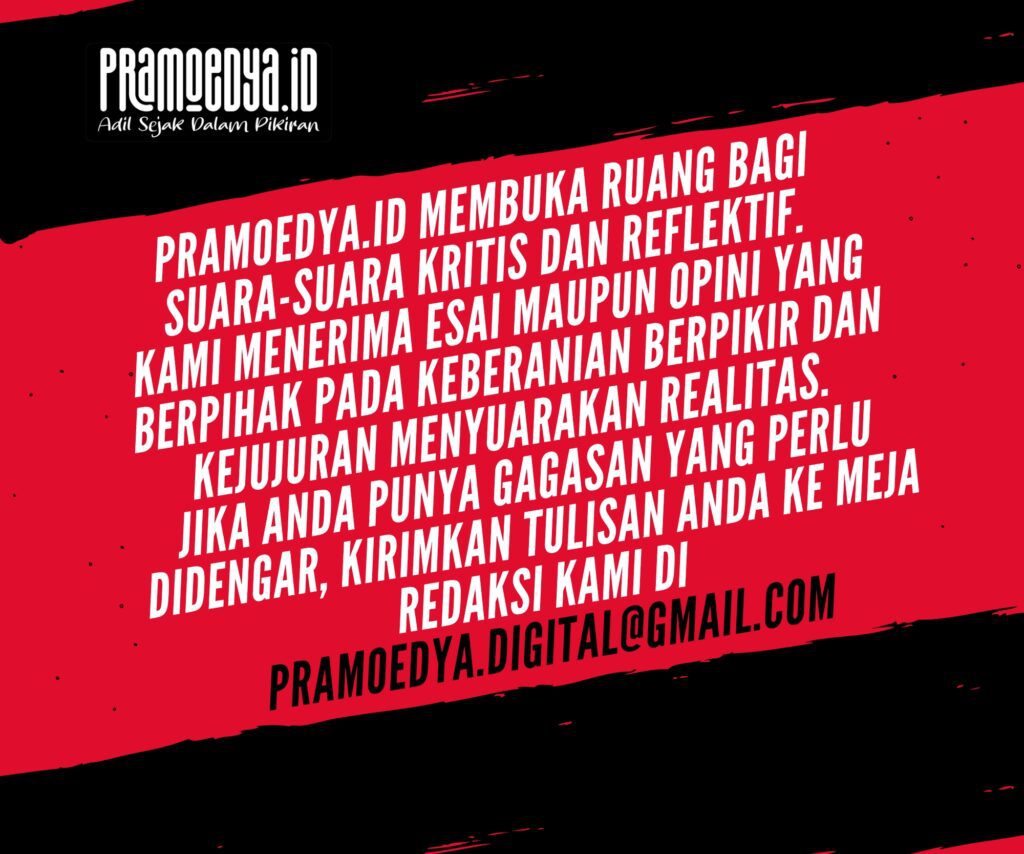Ditulis oleh: Staff Ahli Kemenaker RI, Penta Peturun
Pramoedya.id: “Tanah air bukan hanya tanah, tetapi juga air yang mengalirkan ingatan sebuah bangsa.” Kutipan ini, terukir dari perjalanan saya di Bumi Celebes, Kolaka, pada 16-17 Juni 2025, menjadi pengantar untuk menyelami kisah tentang pit dan ore, lubang ingatan dan bijih harapan yang membentuk lanskap Kolaka hari ini.
Pit dan Ore: Jejak Eksploitasi
Di antara riuh mesin dan debu yang menutup matahari, dua kata tua berbisik di telinga pekerja tambang: pit dan ore. Sederhana, namun di dalamnya bersemayam riwayat panjang manusia menggali isi perut buminya sendiri.
Pit, bagi insinyur tambang, bukan sekadar lubang.
Ia adalah kawah raksasa yang menganga, luka yang sengaja diciptakan untuk membedah rahim alam, menelisik mineral yang tidur di balik cadas. Di situlah manusia menanam keringat, membangunkan pasir, kerikil, bongkah, lalu menimbunnya kembali dengan harapan menjadi emas, nikel, atau sekadar angka devisa negara.
Pit adalah ladang para penambang membanting tulang, membuka ceruk demi ceruk, membentuk tangga raksasa, spiral luka di kulit bumi. Dari kejauhan, ia seperti mangkok raksasa menampung peluh, doa, dan kadang kala, darah. Di lubang itu, setiap orang mengabdi pada logika eksploitasi, berharap memetik remah kemakmuran.
Ore, bijih, adalah janji di ujung ceruk itu. Ia adalah isi dari rahim bumi yang diidamkan. Bijih ini tidak hadir berkilau murni. Ia datang bersama kotoran, batu pengiring, mineral pengganggu. Dari pit, ore diangkut, digilas, dihancurkan, dipisahkan, disaring, dicuci.
Proses panjang ini tak ubahnya ritual pensucian dari bongkah ke butiran, dari kasar ke halus, dari rendah ke bermutu tinggi. Konon, “Dalam diri setiap manusia, ada bijih emas tersembunyi, yang hanya dapat ditemukan dengan melewati penggilingan derita.” Ore pun demikian.
Tanpa pit, ore tak pernah bertemu cahaya. Tanpa deru ekskavator, bijih tetap jadi rahasia abadi di kegelapan tanah.
Namun, begitulah manusia, tak puas dengan cerita permukaan. Kita gali dan gali lagi, lubangi lagi, kuras lagi. Seperti para pencari makna, para penambang pun mencari kesucian di antara lumpur dan batuan keras.
Mencari harga, mencari makan, mencari masa depan. Pit adalah lubang ingatan tentang bagaimana kita merusak dan membangun sekaligus. Ore adalah bijih harapan tentang bagaimana tanah, air, dan udara kita pertaruhkan demi rumah, sekolah, dan perut anak-anak yang menunggu di dapur.
Kita memulai tulisan ini dengan adagium, “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran sebelum bertindak.” begitu kata Pramoedya Ananta Toer.
Jika dikorelasikan dengan tambang, keadilan itu langka. Pit terus digali, ore terus diperas, manusia di pinggir pit seringkali hanya menatap dari jauh, menadah debu, menadah janji.
Maka, biarlah lubang-lubang pit itu juga menjadi lubang renungan sejauh mana kita tega menggali dan sanggup membayar utang kepada bumi? Biarlah ore itu menjadi bijih pengingat. Kekayaan bukan hanya bongkah di truk pengangkut, tetapi bagaimana bijih itu menetes jadi kesejahteraan, jadi jalan raya, jadi sekolah yang tak roboh, jadi rumah yang tak bocor.
Mari kita ajak nurani kita berbisik di lubang pit, “Apa yang kau cari di luar sana, telah lama bersemayam di dalam dirimu.”
Mungkin pit sejati bukan di tanah, tapi di hati manusia, tempat kita mengeruk rakus, lalu pura-pura tak pernah puas. Ore termahal pun takkan cukup menutup lubang keserakahan itu.
Kolaka: Air, Besi, Sabda Terlupakan
Hari ini, di Sungai Watubangga, di pompa-pompa tailing smelter Pomalaa, ingatan itu ditulis lagi bukan dengan tinta, melainkan dengan lumpur, debu nikel, dan angka-angka royalti yang sering salah hitung. Kolaka bagi investor global hanyalah blok laterit, ore saprolit, skema HPAL, RKEF, dan proyeksi nilai ekspor.
Tetapi bagi buruh, petani, dan nelayan di hilir Sungai Watubangga dan Lawulo, Kolaka adalah rumah air, ladang, dan pusaka marga yang sudah tertulis jauh sebelum catatan Belanda bernama Velddagboekditerjemahkan ke format feasibility study modern.
Saya, Penta Peturun, menulis dari perjalanan di pinggir sungai yang keruh, mulai mengering dan berubah kontur.
Menulis agar air punya suara. Menulis agar lumpur punya sabda. Menulis agar pit tambang tidak lebih sakti dari doa di mushola kampung Tambea.
Velddagboek: Pengetahuan Kolonial
Pada akhir abad ke-17, Kolaka disebut Colaca dalam peta Kaart van Celebes terbitan VOC. Tak sepopuler Makassar atau Buton. Colaca hanya titik persinggahan air tawar, rotan, dan damar.
Kontroler VOC tak pernah membangun benteng, mereka membangun loyalitas marga. Sejarawan Belanda menulis, “Colaca is een tussenstation voor bevoorrading.” Stasiun logistik di antara pelabuhan Makassar, Ternate, dan Banda.
Awal 1900-an, Velddagboek Hindia Belanda mencatat potensi bijih laterit di Pomalaa, Kolaka. Insinyur Mijnbouw Dienst menandai blok laterit di bukit-bukit rimba Pomalaa.
Hutan rapat, orang pribumi enggan jadi buruh tambang. Pengetahuan geologi disimpan di brankas Batavia.
1942, Jepang masuk. Belanda lari. Peta geologi tetap diarsip. Jepang gagal menambang karena kalah di Pasifik. Velddagboek pun warisan tak terbaca, dicetak ulang jadi feasibility study perusahaan tambang multinasional zaman republik. “Pit Kolaka hari ini dibor persis di blok Velddagboek kontroler Belanda seabad lalu.” Sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti nama dan logo.
Pomalaa, dari pit hingga High Pressure Acid Leaching (HPAL), adalah proses hidrometalurgi untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dari bijih laterit.
Hari ini, Pomalaa bukan lagi kebun damar dan rotan. Ia adalah pit laterit, jalan hauling, pond sedimentasi, nursery site, HPAL smelter, hingga catatan Pomalaa Growth Project senilai USD 3 miliar. Vale Indonesia melaporkan 3.632 tenaga kerja di site Pomalaa: 2.389 orang Kolaka, 1.240 orang luar, 3 orang TKA, 7 disabilitas (Update 10 Juni 2025).
Sementara itu, Ceria Group, tetangga Vale, juga IPIP, membangun smelter RKEF plus fasilitas green metallurgy, membawa bendera Sustainability. Mereka mempekerjakan 3.653 orang, 2.223 orang Kolaka, 1.430 mitra kerja, dan 211 TKA smelter (Materi HC Ceria 16 Juni 2025).
Demikian juga PT ANTAM, anak kandung negara, lahir dari rencana besar Orde Baru membuka jalan sejak 1974. Tahun itu, suara mesin pertama kali meraung di Pomalaa. Sejak itulah tanah ini resmi jadi salah satu jantung nikel Nusantara, sekaligus urat nadi devisa yang bertahun-tahun menopang neraca ekspor Indonesia.
Antam: Tenaga, Tambang, Janji Tersembunyi
Orang-orang tua di Pomalaa masih bercerita bagaimana jalan tanah dibuka, dermaga kecil dibangun, dan rumah dinas didirikan seperti barak tentara. Dari logam abu-abu yang diciduk dari rahim tanah, Kolaka berubah dari dusun nelayan menjadi kantong pekerja tambang. Dari tahun ke tahun, pabrik feronikel kebanggaan ANTAM, FENI Plant, menyala dan padam silih berganti, mencatat laba dan rugi, menuai pujian dan caci maki.
Tapi satu yang tak berubah: nikel tetap jadi rebutan, dan rakyat di sekitarnya tetap jadi saksi.
Hingga 19 Mei 2025, 3.397 orang menambatkan hidupnya pada ANTAM di UBPN Kolaka. Separuh lebih adalah pekerja borongan yang namanya tercetak di slip upah, tetapi sering hilang dalam rapat rencana jangka panjang. Hanya 27 persen yang berstatus pegawai tetap, sisanya tenaga alih daya yang saban hari menulis cerita sendiri di tanah kaya logam ini, namun kadang pelit berkah. Di Kolaka, rumah dinas berdiri rapat seperti barisan prajurit tua.
Total 1.215 unit rumah tersedia, sebagian besar terisi penuh, hanya 129 unit yang kosong. Orang-orang ini, di balik helm dan rompi tambang, pulang ke rumah yang sama di mana anak menunggu ayah, di mana istri menahan sabar, menanti lelaki yang membagi waktu antara tidur dan lembur.
Data resmi menulis, “dari 24 pegawai level BOD-2 (setingkat Biro), hanya enam orang yang anak kandung tanah Kolaka. Di level Department Head, 28 dari 116 kursi diisi anak daerah,” ujar Muhidin, kini bertugas di Unit Geomin Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Angka ini bagi birokrat di Jakarta barangkali cukup jadi bahan paparan tanda bahwa ‘lokalisasi tenaga kerja’ berhasil. Namun bagi orang tua di tepi jalan Pomalaa, angka ini hanyalah embun pagi yang cepat menguap begitu matahari kesenjangan mulai menyengat.
Upah, regulasi, dan pertanyaan yang tak pernah selesai. Meski jutaan kata PT ANTAM bersumpah di atas kertas bahwa gaji mereka berdiri di percentile ke-75 dibanding 22 perusahaan sejenis. Artinya, di atas laporan, pekerja Kolaka lebih sejahtera dari penambang lain di negeri tambang ini.
Tetapi di warung kopi dekat gerbang pabrik, buruh borongan masih berutang rokok. Sistem remunerasi katanya transparan, adil, objektif. Benarkah begitu bila di meja penggajian yang adil, pekerja tetap dan borongan duduk di kursi sama, namun nasi di piring mereka tak pernah serupa?
IPIP: Nikel, Manusia, Janji Ditepati
Di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, tanah merah meneteskan logam, dan logam itu kini meneteskan harap. Di atas lahan seluas hampir sepuluh ribu hektare itulah sebuah kawasan industri bernama PT. Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) sedang bertumbuh, dibangun dengan debu, peluh, dan kadang sengketa yang membisik di celah-celah pagar proyek. Pomalaa bukan sekadar peta tambang; ia adalah cermin dari sebuah republik yang berkali-kali berikrar untuk hilirisasi, kemandirian, dan tidak lagi menjual bijih mentah ke kapal asing, lalu membeli kembali jadi ponsel dengan harga lipat tujuh.
Area perencanaan ruang lahan 9.384 hektar, area perencanaan tata ruang laut 683 hektar. Lokasi pembangunan di Kecamatan Pomalaa & Tanggetada. Jenis proyek: hidrometalurgi dan pirometalurgi, lithium besi fosfat refinery, prekursor, serta daur ulang baterai. Masa konstruksi: 2022-2027. IPIP lahir dari derap langkah perusahaan tambang raksasa, 70% sahamnya dipegang Huayou Group dan 30% PT Rimau New World yang membawa teknologi hidrometalurgi, pirometalurgi, hingga mimpi daur ulang baterai lithium.
Mereka datang bukan hanya dengan mesin, tapi juga dengan janji memberdayakan manusia lokal, membuka ladang kerja, membangun sekolah kejuruan, hingga menjahit kata “berkelanjutan” di spanduk CSR.
Tujuh proyek fase pertama di dalam kawasan telah dimulai secara bertahap dengan nilai investasi ± 4 miliar dolar dan total karyawan 11.740 orang. Dari tujuh perusahaan dan produk, terdiri dari PT. Kolaka Nickel Indonesia (Nikel Kobalt Hidroksida), PT. Huashuo N Nickel Indonesia (Nickel Matte), PT. Huaxing Nickel Indonesia (Nickel Matte), PT IPIP Port Kolaka (Kapasitas Muatan), PT. Surelyrich Powerplant Indonesia (Kelistrikan), PT. Kolaka Green Energy (Kelistrikan), dan PT. Indonesia Pomalaa Industry Park (Fasilitas Umum).
Fakta di lapangan, awal Juni 2025, sebelum tuntas, jumlah pekerja tercatat 4.906 orang. Delapan puluh tiga persen di antaranya rakyat Indonesia. “Sebagian besar anak-anak Kolaka sendiri, 3.446 jiwa. Sisanya orang-orang muda dari luar kabupaten, mengejar upah, mengejar gelar baru buruh industri nikel. Ada 827 pekerja asing, mayoritas Tiongkok, membawa keahlian teknis yang kata para pengurus Kawasan belum dimiliki insinyur lokal,” pungkas Manager Eksternal Relation PT IPIP, Jilly Philips Makarawung, di hadapan Noel (Wamenaker RI), Bupati Kolaka Hi. Amri, dan Hi. Ahmad Safe’i di ruang rapat UBPN Kolaka, milik PT. Antam (16/06/2025).
Saat ini, jumlah warga lokal yang terserap di IPIP sudah mencapai 80 persen dari total pekerja. Angka itu sudah melebihi ketentuan Perda Nomor 17 Tahun 2023 tentang pemberdayaan tenaga kerja lokal Kolaka, yang mensyaratkan setiap perusahaan menyerap minimal 70 persen pekerja lokal.
“Itu sudah lebih dari 80 persen dari total jumlah tenaga kerja yang ada,” ungkapnya. Kawasan ini menargetkan terminal pelabuhan rampung September 2025.
Dermaga penyangga sudah menapak 1.053 meter. Penimbunan lahan nyaris 90% selesai. Pembangkit listrik tahap pertama dijanjikan hidup November 2026. Sementara orang-orang di tepi proyek menunggu, sambil menyesap kopi, menghitung janji dan kemungkinan upah naik.
Yang patut dicatat, IPIP mencoba merajut hubungan kerja lebih manusiawi. Pelatihan gencar, dari program mentor, murid, pusat kejuruan, hingga pos rekrutmen keliling desa. Mereka meneken MOU dengan Dinas Ketenagakerjaan Kolaka, membentuk bipartit, membangun pos pengaduan, menyediakan ruang salat bagi Muslim. Sekilas, tata kelola SDM mereka tampak rapi di kertas. Namun, pertanyaan kuno kembali muncul: cukupkah lapangan kerja ini untuk menebus rusaknya sungai? Cukupkah pelatihan dan beasiswa membayar tumbangnya hutan?
Dalam agenda besar Poros Maritim Dunia dan hilirisasi industri, IPIP adalah pion di papan catur. Diharapkan bisa memahat Kolaka jadi pilar rantai pasok baterai global.
Bagi rakyat, industri tidak hanya soal output ton per ton. Industri harus mengalirkan kesejahteraan, bukan hanya dividen ke pusat. Industri harus membuat anak-anak kampung punya ruang mimpi, bukan debu batu bara di paru-paru. Kami menulis bukan untuk menghakimi. Kami menulis sebagai pengingat, Republik ini pernah punya mimpi, dan di Pomalaa, mimpi itu dipertaruhkan sekali lagi.
Ceria: Nikel, Saudara, Sejarah Baru
Di tanah Kolaka, logam tidak hanya menetes dari pipa smelter, tetapi juga dari peluh anak-anak kampung yang membayangkan masa depan di pabrik, bukan lagi di kebun. Di sinilah PT Ceria Nugraha Indotama (CNI Group) menancapkan ambisi. Menggerakkan mesin tambang, membangun smelter, dan membuka jalan bagi Indonesia menjadi raja di pasar nikel hijau dunia.
Dua Bersaudara, Penjaga Bara
Di balik gergaji mesin dan cerobong asap smelter Merah Putih, berdirilah dua nama yang kini banyak diperbincangkan: Derian Sakmiwata Sampetoding dan Cherisha Sakmiwata Sampetoding. Mereka pewaris mimpi ayah mereka, Atto Sakmiwata Sampetoding, pengusaha tambang asal Toraja, yang sejak 1992 meletakkan fondasi CNI di bumi Kolaka. Kini, Derian dan Cherisha, lulusan Universitas Griffith, Australia, berbekal amanah keluarga dan bumi Celebes, meramu cita-cita tambang menjadi korporasi kelas dunia.
Mereka bukan sekadar menumpuk ore mentah. Smelter RKEF didirikan dengan kapasitas 252.000 ton feronikel per tahun, ditopang teknologi Rectangular Electric Furnace yang efisien energi dan rendah emisi. Sebuah kebanggaan proyek yang mereka racik sejak 2014 itu, pada 27 April 2025, menyalakan api perdana. Feronikel pertama lahir. Kolaka bergetar.
“Tambang bukan kutukan,” ujar mereka.
Dalam pidato di halaman smelter, Derian merendah, “Alhamdulillah, atas izin Allah, Smelter Merah Putih ini adalah awal, bukan akhir.” Kalimat sederhana, tetapi di baliknya tersembunyi mimpi berlapis: membangun Nickel Matte Converter, Nickel Sulphate Plant, hingga HPAL Plant yang kelak memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), bahan baku baterai kendaraan listrik yang diburu Eropa dan Amerika.
CNI Group bukan hanya membangun pabrik, tetapi membangun harapan lebih dari 600 karyawan, dengan area tambang seluas 6.785 hektar, dan cadangan bijih nikel 295 juta metrik ton.
Rakyat Kolaka berharap pundi-pundi pajak pun menetes deras ke kas negara. Kantor Pajak Pratama Kolaka berkali-kali menempatkan CNI di kursi terhormat sebagai penyumbang pajak tambang terbesar. Derian dan Cherisha, dua nama yang dulunya hanya anak-anak kampus Australia, kini menjadi penentu arah hilirisasi nikel di tanah Sulawesi. Tidak dengan bising pidato, tetapi dengan mesin yang berputar siang-malam.
Smelter Hijau: Janji?
“Green nickel” bukan hanya kata manis. Ceria, nama perusahaan ini selaras dengan #CeriaBerpacu di spanduk korporat, menjanjikan smelter rendah karbon. Teknologi tanur persegi panjang, pasokan listrik bersertifikat Renewable Energy Certificate (REC), hingga pengelolaan limbah tiga prinsip: reduce, reuse, recycle. Di presentasi resmi kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Bapak Immanuel Ebenezer, manajemen menulis, 3.653 pekerja, 2.223 di antaranya lokal Kolaka.
CNI menggandeng BLKK, mendirikan program OSDP, magang di Unhas, Halu Oleo, Sembilanbelas November Kolaka. Hanya waktu yang akan membuktikan, apakah anak-anak Kolaka kelak berdiri di ruang operator smelter sebagai insinyur terampil, atau tetap jadi buruh bongkar muat di pelabuhan ore.
Kini, Smelter Merah Putih berdiri. Ceria Group, dua bersaudara Derian dan Cherisha, menyalakan obor industri hijau di Kolaka. Tapi satu hal yang tak boleh lupa: tambang adalah penakluk masa depan, hanya kalau rakyat di sekitarnya benar-benar menjadi tuan di rumah sendiri. Di bawah langit Kolaka yang berwarna merah bata karena debu nikel, mimpi itu masih merangkak pelan.
Smelter menepati janjinya dengan produk berkualitas, pajak dibayar, CSR dicatat rapi. Tapi sejarah tanah ini, bila diingat: kalau rakyatnya tetap miskin, tambang sebesar apa pun hanya akan jadi kutukan. Maka, dari Ceria lahir cerita.
Dari cerita, rakyat punya daya. Dan semoga dari daya, Kolaka tidak lagi hanya jadi halaman belakang republik tetapi pusat dunia, di mana bijih nikel tak lagi menetes sia-sia.
Vale: Nikel, Janji Bumi Hijau
Di sebuah tikungan waktu, lima puluh lima tahun bukan sekadar angka. Bagi Vale Indonesia, angka itu berderet menjadi tapal jejak langkah raksasa di tanah Sulawesi, di kampung orang-orang tambang, di pinggang gunung dan urat nikel yang tidur di perut bumi. Sejak Sorowako hingga Pomalaa, logam putih keperakan ini bukan hanya membangun pabrik, jalan tambang, dan jalan nasib.
Ia membangun harap dan gundah, membangun sawah dan sumur, membangun janji bahwa bumi yang luka harus disembuhkan sebelum tanah mewariskan kutukan.
Sejak 1920-an, orang-orang asing datang membawa peta geologi. Juli 1968, PT International Nickel Indonesia (INCO) namanya kala itu, menjadi anak kandung Kontrak Karya Republik. Di atas kertas perjanjian itulah, Vale lahir sebagai anak tambang sekaligus penjaga titipan negara dari menambang dengan nilai tambah, memurnikan bijih sebelum ia menyeberangi samudra. Sorowako jadi saksi, sejak 1977 pabrik peleburan berdiri, peresmian yang dihadiri Soeharto sebagai Presiden.
Dari sana, nama INCO bertransformasi jadi PT Vale Indonesia Tbk, mengubah struktur pemilik, tetapi tak gentar menagih tanggung jawab: nikel harus jadi emas hijau, bukan luka basah di lereng hutan.
Kini, Vale menancapkan tonggak baru di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nama proyeknya Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa. Di sini, Vale menggandeng Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. Mereka bersekutu membangun pabrik HPAL (High Pressure Acid Leach) berbiaya US$ 4,5 miliar, mimpi besar yang ditanam di Bumi Mekongga. Targetnya, 120 ribu ton nikel dan 15 ribu ton kobalt per tahun, bahan baku baterai kendaraan listrik yang kian mendominasi jalan raya masa depan.
Vale tidak datang sendirian. Konon, dan semoga terus menjadi nyata, ia membangun, merekrut, mendidik. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 3.600 orang bekerja di Pomalaa. Dari jumlah itu, 2.389 anak Kolaka sendiri, anak kampung yang disulap jadi operator alat berat, teknisi las, juru listrik, hingga petani organik yang tanahnya dibersamai pengetahuan baru.
Ada Sriati, 25 tahun, perempuan tangguh dari Puuroda, Baula. Dulu hanya gadis desa, kini operator ekskavator di Petrosea, mitra Vale. Satu nama di antara ribuan. “Kami patuh pada regulasi nasional dan ILO, termasuk ramah pada gender,” ujar Immanuel Ebenezer, yang biasa dipanggil Noel, saat bertemu manajer HRD Vale, perempuan cerdas bernama Ildha Mawarni N, di Pendopo Bupati Kolaka.
Sebagai Senior HR Project Coordinator, Ildha, namanya sederhana, posturnya tak hendak menantang siapa pun, tapi sungguh, siapa pun yang menganggap HRD itu cuma polisi absen karyawan, orang upahan bos, atau tukang kirim surat PHK, pasti akan terheran jika duduk di seberang meja Ildha.
Ia punya satu hal yang sudah makin langka: integritas. Bagaimana sorot matanya menolak mentah-mentah kompromi pada pelecehan seksual di ruang kerja. Di kantor, di tambang, di pabrik, di ruang-ruang rapat di mana suara perempuan kerap dilunakkan oleh ketakutan, Ildha malah menajamkannya. Ia menolak tunduk. Bukan itu saja.
Perempuan ini, manajer HRD satu ini, merangkul kawan-kawan disabilitas tanpa banyak gembar-gembor. Ia tidak menjadikan inklusi sekadar poster di lobi kantor. Ia menyiapkan kursi, jalan masuk, dan yang lebih penting, ruang setara di hati para buruh.
Noel, begitu orang-orang biasa berteriak memanggil, merasa bersyukur punya kawan seperjuangan sekeras dan secerah Ildha.
“Dua Surat Edaran yang kami terbitkan, soal perlindungan pekerja dari pelecehan dan penegasan hak disabilitas, ia peluk sebagai tanggung jawab. Tidak banyak HRD yang begitu. Biasanya cuma tanda tangan di notulen rapat, lalu hilang ditelan kesibukan bulanan,” ujar Noel dengan senyum bahagia bila mendengar perusahaan yang patuh untuk perlindungan buruh.
Saya percaya bahwa jika satu Ildha saja bisa menyalakan api begini, apalagi jika HRD di ribuan perusahaan menyalakan semangat serupa. Suara yang lahir dari keyakinan bahwa buruh, siapa pun dia, berhak pulang kerja tanpa takut disentuh tanpa izin.
Bahwa yang cacat bukan kawan difabel kita, tetapi sistem dan pola pikir yang membatasi mereka. Noel, yang kadang keras, kadang konyol, tapi selalu jujur di jalan pekerja, mencatat hari ini di dada saya, bahwa Indonesia Maju, Indonesia Emas, Indonesia Terang bukan sekadar mimpi papan iklan. Asal di barisan belakangnya, di antara HRD, buruh, manajer, dan birokrat, tumbuh orang-orang yang berani bertahan menolak pelecehan, merangkul kawan disabilitas, dan berdiri di jalan diversitas ekonomi dan inklusi yang sejati.
Ildha menegaskan sepakat, ratifikasi Konvensi ILO tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja bukan lagi cuma angka di map rapat, tapi nyawa di urat nadi gerakan buruh kita. Dan saya berharap, satu persatu, di tempat lain, Ildha-Ildha baru lahir lagi.
Semoga, malam yang pelan, di antara doa para buruh dan senyum HRD yang lurus jalannya.
Dalam satu barisan, Vale menulis babak tanggung jawab sosial: beasiswa untuk 70 mahasiswa Universitas Sembilanbelas November Kolaka, simulator alat berat senilai Rp 1,2 miliar untuk BLK Kolaka, pelatihan keselamatan dasar untuk 1.302 peserta, pelatihan operator untuk 357 peserta, welder dan electrical untuk puluhan anak muda, serta program PPM yang tidak sekadar basa-basi CSR: pertanian organik, pelatihan herbal, operasi katarak gratis, sumbangan untuk korban kebakaran, anak yatim, hingga revitalisasi pasar tradisional. Semua dijahit dalam satu kata, keberlanjutan.
Namun, di balik haru data dan laporan CSR, sejarah tak pernah lupa menulis pengingat. Ledakan smelter di Morowali beberapa tahun lalu jadi tamparan yang merobek kesadaran industri ini.
Tambang tanpa kendali hanyalah penjara bagi anak cucu, racun bagi sungai, dan racik pilu di dada rakyat. Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dalam setiap sidak dan rapatnya mengingatkan Vale, keselamatan kerja bukan cuma slogan di papan proyek.
“Tak boleh ada nyawa hilang di cerobong. Produktivitas tak boleh menindas keselamatan,” katanya suatu hari di depan pekerja Pomalaa.
Bupati Kolaka, Hi. Amri, pun menekan, Vale harus menanamkan akar di hati rakyat, bukan hanya di bumi tambang. Pajak daerah, lapangan kerja lokal, serapan talenta desa harus dibuktikan dengan data, bukan sekadar brosur manajemen. Hi. Ahmad Safe’i, tokoh Kolaka, mantan bupati dua periode, kini anggota DPR RI, bahkan lebih keras, “Saya yang dulu meneken izin investor masuk ke Kolaka. Jika kalian tak mampu mensejahterakan rakyat, saya murka. Ini tanggung jawab saya di hadapan rakyat dan bumi Kolaka.”
Maka Pomalaa hari ini ibarat kuncup yang menahan mekar. Di balik lahan 5 hektare nursery yang kelak menumbuhkan sejuta bibit, di balik embung sedimen, tambang saprolit, jalan hauling yang meretas bukit, di balik gedung kontrol operasi, tertulis pertanyaan: mampukah tambang modern bertanggung jawab hingga ke akar rumput?
Vale menjawab dengan rapat dan rapih.
Fasilitas nursery di Pomalaa digandengkan dengan Kebun Raya Kolaka, membangun rantai hijau yang akan menampung kembali debu tambang menjadi napas daun.
Infrastruktur didorong: jalan tambang, jembatan, workshop, gedung kontrol. Dari tambang saprolit dan limonit, penambangan hijau dijanjikan jadi barometer industri nikel rendah karbon Nusantara.
Tapi semua cerita ini pada akhirnya akan diuji ketika bijih diangkut, emisi diolah, limbah dijinakkan, bibit ditanam di bekas lubang tambang, dan rakyat menatap tagihan listrik kendaraan listrik di rumah-rumah mereka. Lima puluh lima tahun Vale Indonesia seolah membuka kitab panjang bahwa menambang di Indonesia bukan hanya soal untung dan rugi.
Ini soal tanah leluhur, soal air yang turun ke sawah, soal orang tua yang ingin anaknya sarjana, bukan buruh tambang selamanya. Soal tambang yang tak lagi jadi kutukan, melainkan berkah yang meninggalkan warisan hijau. Maka biarlah nikel menyeberang benua, baterai menjelma mobil, dan Kolaka menjadi catatan, di sini logam diselipkan doa, agar bumi tetap hijau, agar tambang tidak berujung nyawa yang tergeletak di tanah merah.
Investor datang dengan proposal karbon netral, tailing recycling, dan janji “sungai tetap jernih”. Namun, di Tambea, sawah berubah warna. Di Mandonga, air sumur keruh. Di Bungkutoko, nelayan kehilangan tangkapan. Rakyat kehilangan sawah, tetapi belum punya saham.
Saksi sungai yang meredup, menjadi pengetahuan di warung kopi. Apa kata dashboard CSR? “Zero incident. 100% compliance.” Apa kata warung kopi Mandonga? “Pak, sumur di kampung saya bau besi. Anak gatal, air asin. Pit makin luas, pungli makin banyak.”
Sahabat saya, Prof. Robertus Robet menulis, Ekosipasi = emansipasi ekologis + revolusi pengetahuan rakyat. Epistemologi sungai tidak lahir dari kantor AMDAL, melainkan dari mulut buruh borongan, status Facebook istri buruh, dan video TikTok sopir dump truck. Inilah jurnal lumpur yang tak diajarkan di kursus sertifikasi tambang. Di Mandonga, buruh menyatakan “Sumpah Air dan Besi.” Isinya curhatan upah, pungli rekrutmen TKA, dan keluhan air keruh. Negara kadang hadir di rapat MoU investor, tetapi absen di teras rumah rakyat yang menggali sumur kering.
Political Ecology: Untung dan Tanggung Jawab
Blaikie dan Brookfield (1987) menegaskan: Degradasi bukan bencana alam, tapi lahir dari konflik kuasa. Immanuel Wallerstein (1974) mengemukakan teori dunia core-semi periphery-periphery. Indonesia, dalam konteks ini, tetap periphery.
Bahan mentah ke core. Profit dipetik di bursa saham global. Hilirisasi smelter Morosi, Pomalaa, Weda Bay, adalah buku teks world system theory yang diperagakan di tanah orang Tolaki. Ore mentah diambil, smelter hanya semi finished product, green label dicap Eropa, royalti tercatat di PNBP pusat. Rakyat di pinggir tailing tetap menunggu ganti rugi sawah yang lama.
Jalan Tengah: Pit, Kebun, Sungai
“Tanah adalah pusaka. Air adalah lidah bumi. Siapa merusak, menanggung saksi di Mahsyar.”
Seharusnya, rakyat hulu mendapat 20% saham tambang milik koperasi desa, mendapatkan royalty blockchain, 30% royalti ke Dana Desa, transparan, tanpa pungli. Menciptakan Smelter Hijau: 50% energi PLTS, tailings recycling, Net Zero 2035. Selain itu, perlu adanya Citizen Audit, Komite audit rakyat, sensor IoT terbuka publik. Maka, lakukan Reklamasi Spiritual: Pit ditutup kebun rakyat, sungai dipulihkan untuk ziarah. Sebagai sumpah air dan besi menjadi do’a di pinggir Pit. “Lubang di tanah adalah lubang di dada rakyat, Air keruh pun membawa hikmah, bila engkau sabar membersihkan.”
Sumpah Air dan Besi Kolaka: “Sungai akan kembali jernih, Pit akan jadi kebun rakyat, Royalti akan membiayai sakit warga dan sekolah anak kampung, Smelter hanya boleh hidup jika air hidup.” Hari ini pit Pomalaa makin luas. Velldagboek makin kuno. Namun epistemologi rakyat makin tajam: mereka melek arsip, melek pungli, melek sungai. Rakyat tidak anti pit. Rakyat hanya ingin pit punya penutup dan air punya ayat suci. Kolaka tidak butuh janji. Kolaka butuh, Jalan Tengah Modal dan Sawah. Jalan Tengah Pit dan Sungai. Jalan Tengah kata dan adab.
Wamenaker: Ijazah, Usia, Kutukan SDA
Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, bicara lugas dalam kunjungan ke Kolaka (16 Juni 2025). Di depan jajaran manajer HR Antam, IPIP, Vale, dan Ceria, “Penahanan ijazah itu tidak ada toleransi, titik. Surat Edaran sudah keluar, pelanggaran pidana. Sama halnya batas umur, saya perintahkan perusahaan di Kolaka, Morosi, dan Konawe, jangan lagi tulis syarat ‘maksimal usia.’”
“Kolaka ini kaya raya. Kaya bijih nikel, kaya sungai, kaya sawah. Kalau tidak dikelola untuk kesejahteraan rakyat Kolaka dan juga buruh dalam penegakan norma ketenagakerjaan, K3, dan pemenuhan hak buruh, maka Kolaka hanya akan jadi Kutukan Sumber Daya Alam, bukan berkah SDA.” Dalam catatan resmi Kemenaker (Lampiran Kunjungan UBPN Kolaka 16 Juni 2025), Immanuel menegaskan audit penuh kepatuhan Norma Kerja, K3, dan sistem pembayaran upah.
Tidak boleh lagi buruh borongan dilepas tanpa BPJS Ketenagakerjaan. Tidak boleh lagi buruh direkrut via pungli jalur mandor.
Demikian juga kata Hi. Amri, Bupati muda Kolaka, bicara tanpa podium tinggi, penyerapan tenaga kerja lokal.
Beliau meneken Perda nomor 19 tahun 2024 tentang Penyerapan Tenaga Kerja Lokal. Bunyinya keras, 70% tenaga kerja proyek tambang wajib warga Kolaka. “Tenaga kerja di Kolaka ini harus diberdayakan, jika tidak, saya bersama masyarakat akan turun langsung mempertanyakan ini. Komitmen pemerintah daerah, tidak ada tawar menawar terkait isu tenaga kerja lokal,” tegasnya. Yang akal-akalan lewat vendor titipan, blacklist kontraktor.
Juga soal membayar pajak, “Hasil tambang ini bukan hanya untuk smelter dan bursa Shanghai. Pajaknya harus masuk kas daerah. Jangan main bypass ke pusat semua. Pajak daerah artinya jalan kampung bagus, sekolah gratis, beasiswa anak sekolah. Bukan hanya sakit, bahkan apabila ada warga yang masuk rumah sakit dibiayai juga pendamping si sakit ketika dirawat, ini harga mati!”
Hal ini juga ditegaskan oleh “Ayah Kolaka” di depan rakyat dan bumi, Hi. Ahmad Safei. Bagi orang Kolaka, ia “ayah” yang pernah meneken perjanjian awal dengan investor tambang. Kini ia duduk di DPR RI Komisi IX, mengawasi Ketenagakerjaan dan perlindungan buruh dari Senayan.
Di hadapan kami, beliau bergetar, “Saya yang pertama meneken lampu hijau izin investor masuk ke Kolaka. Kalau kalian gagal mensejahterakan rakyat Kolaka, saya murka. Murka di hadapan rakyat. Murka di hadapan bumi.”
Rakyat Membaca Peta, Bukan Data
Robertus Robet, profesor ekosipasi, pernah menulis, “Emansipasi ekologis tidak cukup bicara di ruang seminar. Ia harus hidup di teras rumah dan warung kopi.” Di Kolaka, epistemologi rakyat lahir dari overlay peta Velldagboek Belanda dengan blok IUP modern. Masyarakat Tambea memindai batas adat dengan GPS. Komite Adat mencatat jalur sungai pusaka yang kini jadi alur tailing. Warung kopi Mandonga jadi markas sumpah air dan besi, sekelompok buruh, nelayan, dan aktivis lokal yang memegang sensor kualitas air, bukan hanya sertifikat AMDAL. Mereka adalah penjaga sungai yang berbisik.
Air keruh, pit makin dalam, suara rakyat makin keras. Lubang di tanah adalah lubang di dada rakyat. Air keruh akan jernih bila engkau sabar membersihkan, sabar menulis. Tanah pusaka, sungai pusaka, amanah iman dan akal.
“Tanah adat adalah kitab. Sungai adalah kalam Tuhan. Siapa menulis di atasnya dengan dusta, kelak menanggung saksi di hadapan Allah.” Sejarah tidak pernah mati.
Kolaka, Air Mata, Sumpah Tak Berujung
Sejarah tidak pernah mati. Yang mati hanyalah ingatan yang tak diasah, suara yang tak berani diucapkan, atau nurani yang terbius janji-janji manis. Kolaka adalah cermin bagi kita semua: sebuah tanah yang kaya, namun menyimpan luka. Sebuah bangsa yang bermimpi besar, namun kerap alpa pada mereka yang paling dekat dengan bumi.
Maka, biarlah Sumpah Air dan Besi Kolaka ini menjadi penutup sekaligus pembuka. Penutup bagi babak eksploitasi tanpa akuntabilitas. Pembuka bagi era baru di mana pembangunan bukan hanya soal angka di neraca, tetapi juga senyum di wajah rakyat, kejernihan sungai, dan hijaunya kembali hutan yang terenggut.
Sungai akan kembali jernih, pit akan jadi kebun rakyat, royalti akan membiayai sakit warga dan sekolah anak kampung.
Smelter hanya boleh hidup jika air hidup. Hari ini pit Pomalaa makin luas. Velddagboek makin kuno. Namun epistemologi rakyat makin tajam terlihat dari mereka melek arsip, melek pungli, melek sungai. Rakyat tidak anti pit. Rakyat hanya ingin pit punya penutup dan air punya ayat suci.
Kolaka tidak butuh janji. Kolaka butuh Jalan Tengah Modal dan Sawah. Jalan Tengah Pit dan Sungai. Jalan Tengah kata dan adab.
Inilah sumpah yang terpatri, sejarah tidak pernah mati, yang mati hanyalah harapan jika kita berhenti bersuara. Kolaka, dengan air mata dan bijih nikelnya, adalah panggilan.
Panggilan untuk keadilan, panggilan untuk keberpihakan, dan panggilan untuk sebuah masa depan di mana tanah air benar-benar menjadi berkah bagi seluruh bangsanya, bukan sekadar komoditas yang diperas hingga kering. Tabik Pun. (*)