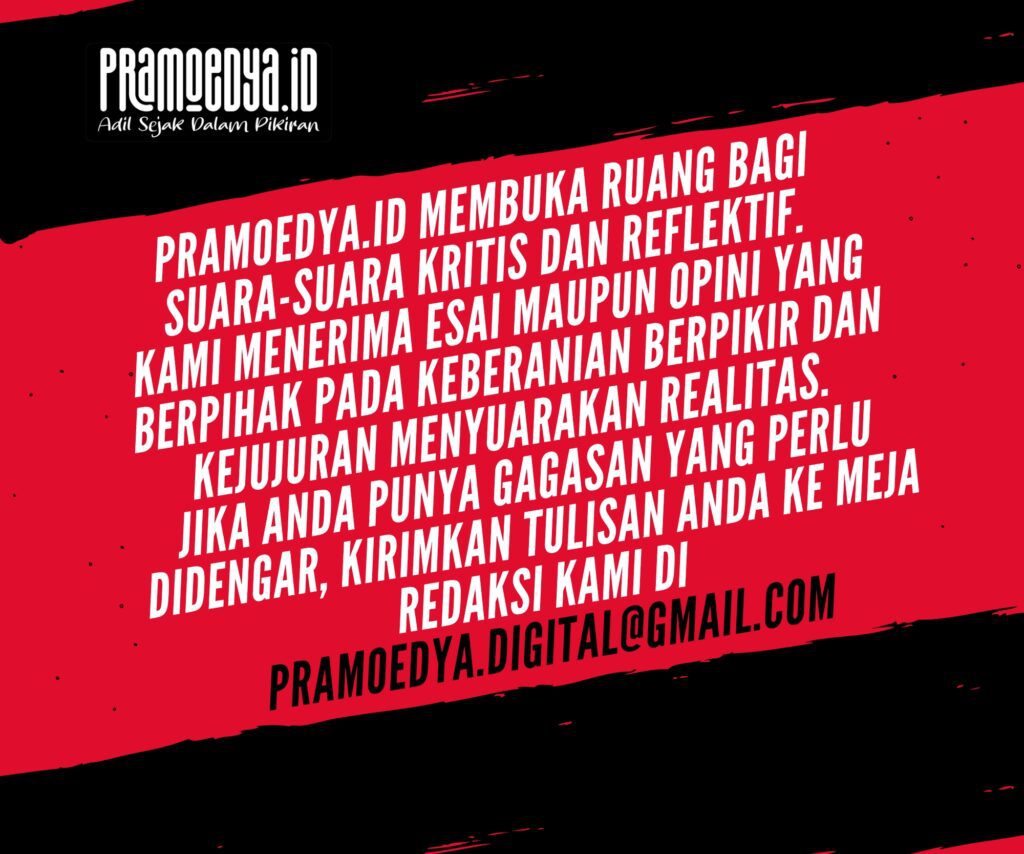Oleh: Peksyaji Karto Prawiro (Wakil Ketua I Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Depok)
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tampak semakin percaya diri mengambil peran penting dalam peta industri global. Salah satu strategi yang mencolok adalah kebijakan hilirisasi nikel, sebuah upaya sistematis untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan membangun ekosistem industri pengolahan di dalam negeri.
Pramoedya.id: Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai tonggak menuju kedaulatan ekonomi. Dan memang, data menunjukkan capaian yang patut diperhitungkan, pertumbuhan PDB meningkat 1,5 persen, lebih dari setengah juta lapangan kerja tercipta, dan ekspor produk nikel olahan melonjak signifikan.
Namun di balik optimisme itu, ada urgensi untuk bersikap lebih kritis. Hilirisasi bukan sekadar soal industrialisasi. Ini soal arah pembangunan, apakah benar berkelanjutan, adil, dan memperkuat kedaulatan nasional, atau hanya ilusi pertumbuhan yang menyembunyikan ketimpangan dan ketergantungan baru?
Ketergantungan Baru dan Risiko Geopolitik
Salah satu ironi dari hilirisasi nikel Indonesia adalah ketergantungannya pada investasi asing, terutama dari Tiongkok. Perusahaan-perusahaan dari negeri Tirai Bambu mendominasi pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan nikel di Indonesia. Dari kacamata pragmatis, kerja sama ini membawa keuntungan teknologi, modal, dan pasar. Namun, ketergantungan pada satu negara membuka risiko strategis, terutama dalam dinamika geopolitik yang kian memanas.
Situasi ini sebagai bentuk “poli-alignment”, di mana Indonesia harus terus menyeimbangkan kepentingan di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dalam sektor energi bersih. Jika tak dikelola hati-hati, ketergantungan ini justru bisa menggerus kemandirian nasional yang ingin dicapai melalui hilirisasi.
Dampak Ekologis yang Kerap Terabaikan
Sisi lain yang sering luput dari perbincangan adalah dampak lingkungan dari proses hilirisasi. Produksi nikel memiliki jejak karbon tinggi dan potensi kerusakan ekologis yang serius. Emisi karbon dari proses ini cukup signifikan dan berisiko mencemari udara, air, dan tanah. Sementara itu, pertambangan laterit nikel meninggalkan kerusakan permanen pada lanskap dan ekosistem lokal.
Upaya mitigasi memang ada, mulai dari eksplorasi energi terbarukan hingga regulasi ketat. Namun, pelaksanaannya masih jauh dari memadai. Tanpa penegakan aturan yang konsisten, Indonesia berisiko terjebak dalam paradoks, yakni membantu dunia beralih ke energi bersih sambil merusak lingkungannya sendiri.
Ketimpangan Manfaat dan Tata Kelola yang Lemah
Hilirisasi sering dipromosikan sebagai pembuka lapangan kerja dan motor pertumbuhan. Namun, pertanyaannya: siapa yang paling merasakan manfaat itu?
Distribusi manfaat hilirisasi belum merata, bahkan memperkuat konsentrasi keuntungan di wilayah tertentu. Masyarakat lokal harus dilibatkan, bukan sekadar menjadi penonton atau korban. Sayangnya, transparansi dan partisipasi publik masih minim. Jika ini dibiarkan, kebijakan yang dimaksudkan untuk membawa kesejahteraan justru bisa memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Peluang dalam Rantai Pasok Global
Secara strategis, posisi Indonesia di peta transisi energi global tak bisa diremehkan. Nikel adalah bahan utama baterai kendaraan listrik (EV), dan Indonesia punya cadangan terbesar di dunia. Pemerintah membentuk PT Baterai Indonesia serta konsorsium BUMN untuk membangun ekosistem baterai dari hulu ke hilir.
Sektor stainless steel berbasis nikel cukup berkembang, kemampuan Indonesia memproduksi baterai kelas dunia masih tertinggal. Tanpa lompatan di bidang riset dan pengembangan SDM, kita hanya akan menjadi eksportir bahan setengah jadi, bukan penguasa teknologi bernilai tambah tinggi.
Tekanan dari Hukum Internasional
Hilirisasi juga menghadapi tantangan dari luar negeri. Pelarangan ekspor bijih nikel mentah oleh Indonesia digugat Uni Eropa di WTO. Ini menunjukkan ketegangan antara kedaulatan negara atas sumber dayanya dan komitmen dalam perjanjian dagang internasional.
Saya pribadi mendukung hak Indonesia untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri. Namun, strategi diplomasi dan hukum tetap dibutuhkan agar tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan yang bisa melemahkan posisi tawar kita.
Menyempurnakan, Bukan Membatalkan
Hilirisasi bukan kebijakan yang keliru. Ia justru salah satu langkah paling ambisius dalam sejarah ekonomi Indonesia. Tapi ambisi saja tidak cukup. Hilirisasi harus diarahkan untuk memperkuat inklusi sosial dan mendukung transisi energi berkelanjutan.
Pemerintah perlu bergerak dalam tiga arah. Memperkuat regulasi lingkungan agar pembangunan industri tidak merusak ekosistem. Mendorong tata kelola yang transparan dan partisipatif agar masyarakat lokal terlibat aktif. Serta meningkatkan kapasitas teknologi dan SDM agar kita tak hanya jadi mitra, tapi penggerak utama.
Hilirisasi Bukan Sekadar Angka
Kita tak bisa menilai hilirisasi hanya dari angka pertumbuhan dan lonjakan ekspor. Harus ada pertanyaan lebih mendasar: siapa yang paling diuntungkan? Apa yang dikorbankan? Dan apakah arah pembangunan ini benar-benar menuju kedaulatan?
Indonesia punya peluang besar menjadi aktor penting dalam ekonomi hijau dunia. Tapi peluang itu hanya bisa diwujudkan jika pembangunan dijalankan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Di situlah ujian sejati dari hilirisasi hari ini.(*)