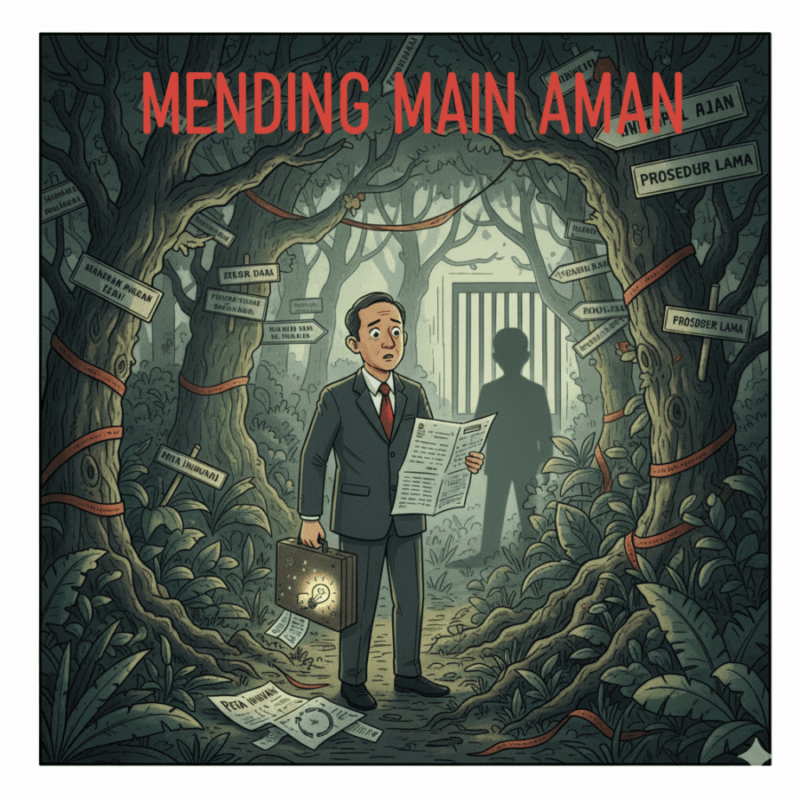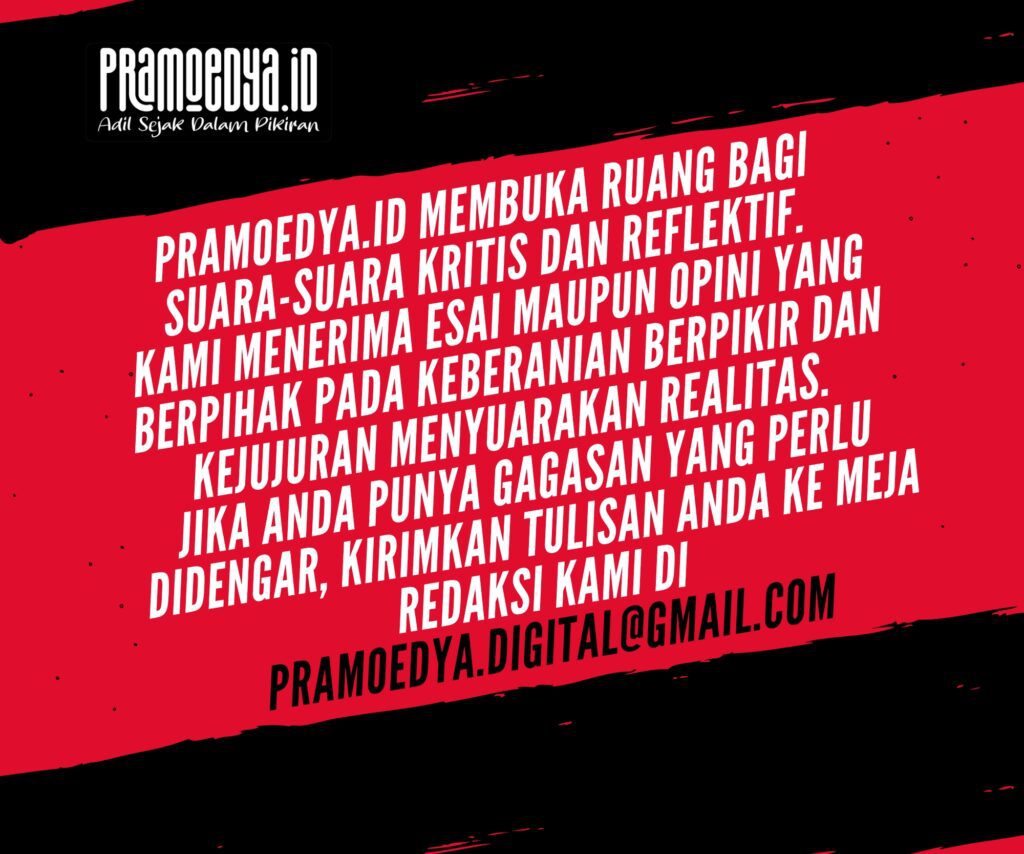Pramoedya.id: Di Indonesia, pejabat inovatif sering kali seperti orang yang masuk hutan tanpa peta. Mereka punya niat baik, ide cemerlang, bahkan visi jauh ke depan. Tapi begitu melangkah keluar jalur aturan lama, risiko hukum langsung mengintai. Akibatnya, banyak pejabat memilih bermain aman alias diam, rutin, dan birokratis. Karena di negeri ini, berinovasi bisa berarti menyiapkan diri untuk masuk penjara. Tidak percaya? Mari kita urai.
Dahlan Iskan: Visioner yang Keburu Dikriminalkan
Ambil contoh Dahlan Iskan. Saat menjabat Menteri BUMN era Presiden SBY, ia berambisi mendorong mobil listrik nasional. Tahun 2013, 16 unit mobil listrik dipamerkan di KTT APEC Bali, didanai lewat dukungan beberdapa BUMN dengan total anggaran Rp32 miliar. Idenya keren: Indonesia bisa tampil sebagai pemain masa depan di industri otomotif.
Tapi kenyataannya pahit. Mobil yang dihasilkan masih prototipe, belum siap pakai. Proyek itu dipersoalkan karena tidak melalui tender resmi. Hasil audit menyebut ada kerugian negara lebih dari Rp17 miliar. Dahlan pun sempat jadi tersangka, meski kemudian lepas. Ironi besar muncul di sini: hari ini, mobil listrik justru digembar-gemborkan pemerintah sebagai program unggulan. Apa yang dulu dianggap “kesalahan”, kini menjadi kebijakan resmi. Dahlan hanya terlalu cepat.
Inovasi Alias Cari Gara-Gara
Kisah serupa, meski dengan skala berbeda, dialami pejabat lain. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ketika memimpin Jakarta, memperkenalkan sistem e-budgeting. Tujuannya mulia berupa transparansi, agar tak ada lagi “anggaran siluman”. Namun langkah ini justru membuat DPRD marah besar. Alasannya, sistem itu belum diatur jelas dalam regulasi lama. Inovasi terbukti bermanfaat, tetapi karena belum ada payung hukum, Ahok menghadapi perlawanan keras.
Di Surabaya, Tri Rismaharini membuat taman-taman kota, memperbaiki sistem pengelolaan sampah, dan memindahkan banyak pelayanan ke jalur online. Warga merasakan manfaat, tapi DPRD sibuk mempermasalahkan prosedur dan dasar hukum. Risma sampai pernah menangis dan ingin mundur, karena langkah-langkah barunya selalu diadang.
Ridwan Kamil juga tidak luput. Dari Bandung hingga Jawa Barat, ia mempopulerkan aplikasi layanan publik dan ruang kreatif. Hasilnya disambut publik, tapi aparat pengawas bolak-balik menyoal legalitas. Lagi-lagi, masalahnya bukan pada niat, melainkan pada payung hukum yang belum ada.
Inovasi Mati Sebelum Pubertas
Bukan berarti pemerintah tidak punya stok gagasan. Sejak KemenPANRB membuka kompetisi inovasi pelayanan publik, ribuan ide muncul setiap tahun. Tahun 2014 ada 515 inovasi. Dua tahun kemudian melonjak jadi 2.476, lalu stabil di angka tiga ribuan. Angka ini menunjukkan antusiasme birokrasi untuk berkreasi.
Tapi angka partisipasi tidak sebanding dengan keberlanjutan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2022), hanya sekitar 12 persen inovasi yang berlanjut dan dipakai ulang di daerah lain. Mayoritas berhenti setelah pilot project, tersendat karena tidak ada anggaran lanjutan atau dasar hukum yang mendukung. Jadi, banyak ide bagus mati muda sebelum tumbuh besar.
Aturan Itu Tajam ke Inovasi, Tumpul ke Korupsi
Kenapa inovasi sulit bertahan? Masalahnya ada di kultur hukum. Di Indonesia, asas legalitas jadi pagar keras, semua pengeluaran negara harus punya dasar aturan yang jelas. Inovasi, karena definisinya adalah sesuatu yang baru, otomatis sering kali belum punya pijakan hukum.
Di atas kertas, ada tiga jenis audit dari keuangan, kepatuhan, dan kinerja. Tetapi di lapangan, yang paling ditekankan adalah kepatuhan prosedural. Jadi, kalau prosedur sedikit saja meleset, pejabat bisa kena jerat hukum, meski manfaat inovasinya nyata. Belum lagi soal politik dari inovasi yang merombak sistem lama sering mengganggu kenyamanan elite yang diuntungkan dari status quo. Hasilnya, inovasi bukan hanya ditolak, tapi bisa sengaja dijadikan kasus.
Wajar Kalau Pejabat Memilih Diam
Jika dipikir rasional, pejabat lebih aman bermain sesuai aturan lama. Biaya politik dan hukum terlalu tinggi untuk mencoba hal baru. Satu kesalahan administrasi bisa berujung jeruji. Inilah yang membuat banyak pejabat memilih jalur paling aman: jalankan rutinitas, jangan macam-macam. Rakyat mungkin bosan dengan birokrasi lamban, tapi bagi pejabat, stagnasi berarti selamat.
Padahal ada jalan keluar. OJK misalnya, punya regulatory sandbox untuk fintech. Start-up boleh mencoba ide baru dalam ruang terbatas, sambil didampingi regulator, sebelum aturan final dibuat. Kenapa model serupa tidak dipakai di pemerintahan umum? Pejabat bisa diberi ruang pilot project, dengan aturan sementara yang melindungi dari jeratan hukum, selama transparan dan melibatkan pengawasan publik.
Kejaksaan juga punya fungsi sebagai pengacara negara. Mereka bisa dilibatkan sejak awal, memberi pendapat hukum sebelum proyek jalan. Dengan begitu, pejabat punya pegangan, bukan hanya insting. Audit pun sebaiknya bergeser menilai manfaat, bukan sekadar checklist prosedural.
Butuh Resolusi Birokrasi Jika Ingin Maju
Dari kisah Dahlan sampai Risma, dari data ribuan inovasi yang berhenti di tengah jalan, satu pola terlihat jelas di Indonesia, inovasi birokrasi sering kalah oleh aturan yang kaku. Kalau ini dibiarkan, pejabat akan terus memilih aman. Kita mungkin tidak akan melihat banyak Dahlan baru, tapi juga tidak akan melihat terobosan besar yang bisa mendorong Indonesia melompat maju. Berkaca dari mereka pada intinya sistem republik ini Memang dibuat ‘miskin’ inovasi.
Pertanyaan akhirnya sederhana: apakah kita rela birokrasi kita stagnan demi aman dari jeruji, atau berani menciptakan ruang aman bagi pejabat yang mau mencoba sesuatu yang baru? (*)